KOMPARASI.ID – Setiap musim hujan datang, Gorontalo kembali mengulang cerita yang sama. Sungai meluap, sawah terendam, jalan-jalan berubah menjadi aliran coklat keruh. Banjir seperti menjadi musim yang tak lagi mengenal kalender.
Di saat yang sama, di kawasan hulu, alat berat merayap naik ke lereng-lereng perbukitan. Lapisan tanah dikupas, vegetasi dibuka, dan batuan dibelah untuk mengejar satu komoditas, emas.
Di tengah geliat ekonomi tambang yang menjanjikan kesejahteraan instan, Gorontalo berdiri di sebuah persimpangan mendasar, berapa harga ekologis yang harus dibayar untuk setiap gram emas yang diangkat dari perut bumi?
Hulu yang Terbuka, Hilir yang Menanggung
Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap wilayah perbukitan dan hutan di Gorontalo meningkat. Di Pohuwato dan Boalemo, aktivitas pertambangan skala besar maupun kecil terus bergerak ke kawasan yang secara ekologis berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Di Bone Bolango, pertambangan rakyat berkembang dengan pola berbeda, tetapi tetap memberi tekanan pada bentang alam hulu.
Gorontalo secara geografis dikenal sebagai wilayah dengan bentang alam cekungan. Kondisi ini membuat limpasan air dari kawasan hulu cepat terkumpul di dataran rendah. Ketika hujan dengan intensitas tinggi turun, risiko banjir meningkat secara signifikan.
Menurut akademisi lingkungan dari Universitas Negeri Gorontalo, Sri Sutarni Arifin, pembangunan di wilayah seperti Gorontalo semestinya berbasis pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Konsep pembangunan berkelanjutan itu sudah ada dalam dokumen perencanaan seperti KLHS, RTRW, dan RDTR. Jika dijalankan dengan benar, peluang untuk meminimalisir dampak jauh lebih besar,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial. Hulu dan hilir harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem.
Aktivitas pengerukan dan pembukaan lahan pada lereng dengan kemiringan tinggi meningkatkan potensi longsor, mempercepat sedimentasi anak sungai, dan memperbesar kemungkinan luapan ketika debit air hujan meningkat.
Sejumlah riset di wilayah DAS tropis menunjukkan bahwa deforestasi sebesar 10-20 persen saja dapat meningkatkan beban puncak aliran hingga 30-50 persen.
Artinya, frekuensi banjir yang sebelumnya terjadi lima tahunan bisa berubah menjadi dua tahunan, bahkan tahunan.
“Kalau hutan dihilangkan lalu diganti dengan infrastruktur seperti tanggul atau normalisasi sungai, dan biayanya sangat besar, maka nilai jasa ekosistem hutan itu sebenarnya jauh lebih mahal,” kata Sri.
Moratorium atau Percepatan?
Sri Sutarni menegaskan bahwa dalam kondisi ekstrem ketika kerusakan berlangsung masif, pemerintah perlu mempertimbangkan moratorium tambang, terutama di kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai yang memiliki fungsi vital.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi data konsesi dan dana rehabilitasi lingkungan dalam bentuk escrow fund yang terpisah dari dana operasional perusahaan.
Tanpa komitmen kebijakan berbasis prinsip kehati-hatian, Gorontalo berisiko menanggung beban ekologis jangka panjang yang jauh lebih mahal dibanding manfaat ekonomi jangka pendek.
Janji Kesejahteraan dan Siklus yang Singkat
Di sisi lain, tambang hadir dengan narasi yang sulit ditolak, kesejahteraan. Uang berputar cepat. Dalam hitungan hari, seorang pekerja tambang emas bisa memperoleh pendapatan setara setengah bulan penghasilan sektor lain.
Desa yang sebelumnya sepi mendadak ramai. Warung, bengkel, dan usaha jasa bermunculan.
Di Pohuwato, proyek besar seperti Pani Gold Project menjadi simbol masuknya investasi berskala industri. Bersamaan dengan itu, pertambangan tanpa izin (PETI) juga tumbuh di berbagai titik. Daya tarik ekonomi tambang menjangkau hampir semua lapisan masyarakat.
Perwakilan Japesda, Renal Husa, menyebut ketergantungan masyarakat pada tambang sebagai respons atas ketidakpastian ekonomi yang lebih dulu terjadi.
Di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia, sedimentasi irigasi menyebabkan sawah gagal panen. Sedimen bahkan telah mencapai estuari. Beberapa jenis ikan mulai berkurang, memukul pendapatan nelayan.
“Ketika sektor pertanian dan perikanan tidak lagi memberi kepastian, masyarakat mencari alternatif. Tambang dianggap solusi. Tapi pilihan itu justru berpotensi memperparah kerusakan,” ujarnya.
Ia menilai negara belum sepenuhnya hadir menengahi persoalan ini. Masyarakat dibiarkan bertahan sendiri di tengah rusaknya lahan dan menyempitnya ruang tangkap.
Dari Agraris ke Ekstraktif
Pergeseran dari pertanian dan perikanan menuju tambang bukan sekadar perubahan jenis pekerjaan. Ia mengubah struktur sosial desa.
Ketika mayoritas warga bertani atau melaut, relasi sosial cenderung berbasis solidaritas dan gotong royong. Namun saat tambang masuk, muncul kelompok baru yang memiliki akses pada modal, alat berat, atau kedekatan dengan pemegang izin. Di sisi lain, sebagian warga hanya menjadi buruh dengan posisi tawar rendah.
Ketimpangan pendapatan menjadi lebih kasat mata. Dalam waktu singkat, sebagian orang melonjak secara ekonomi, sementara yang lain kehilangan lahan atau ruang hidup.
Relasi sosial berubah lebih transaksional.
Orientasi hidup bergeser dari keberlanjutan jangka panjang ke hasil cepat dan keuntungan instan. Generasi muda mulai memandang pertanian sebagai pilihan yang tidak menjanjikan.
Dalam situasi seperti ini, desa berpotensi terbelah antara kelompok yang mendukung tambang dan yang menolak. Konflik tidak hanya terjadi antara warga dan perusahaan, tetapi juga antar sesama warga.
Perempuan dan Kelompok Rentan di Pinggir Perubahan
Meski belum ada riset spesifik di wilayah tersebut, Renal menilai secara umum aktivitas tambang cenderung lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki.
Perempuan yang sebelumnya terlibat dalam pertanian atau pengelolaan hasil kebun terdampak ketika ruang produksi menyempit.
Kelompok rentan, keluarga miskin, lansia, anak-anak, warga tanpa lahan menjadi pihak yang paling sulit beradaptasi ketika kualitas air, udara, dan tanah menurun. Dalam perubahan sosial yang cepat, suara mereka kerap tidak terakomodasi dalam pengambilan keputusan.
Jika tata kelola tidak inklusif, aktivitas pertambangan berpotensi memperlebar ketimpangan sosial di tingkat desa.
Ketika Adat Tak Lagi Menjadi Rambu
Pemerhati sejarah, budaya, dan adat Gorontalo, Ali Mobiliu, menilai persoalan eksploitasi pertambangan yang masif saat ini tidak lepas dari melemahnya peran sistem adat dalam tata kelola daerah.
Menurutnya, pemerintah belum secara optimal menghidupkan kembali mekanisme adat yang sejak lama menjadi rambu sosial dan moral dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam.
Ia menyebut, seharusnya Pemerintah Provinsi Gorontalo merumuskan kembali Bandhayo Poboide di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai forum kerapatan adat.
Ali menjelaskan, Bandhayo Poboide pertama kali dilaksanakan pada abad ke-14 pada masa Raja Gintulangi. Dari situ lahir prinsip “Tuwawu duluwo limo lo pohala’a”, yang menjadi dasar pengaturan kehidupan sosial, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dalam pandangannya, jika prinsip-prinsip adat tersebut ditegakkan, maka aktivitas pertambangan tidak akan berlangsung secara serampangan karena terikat oleh norma dan rambu adat.
Ia menilai, ketiadaan penguatan hukum adat hari ini melahirkan standar ganda. Investor atau pemodal relatif mudah mendapatkan akses, sementara masyarakat lokal yang mengelola tanahnya sendiri justru kerap dicap ilegal atau masuk kategori PETI karena tidak memiliki izin formal dari negara.
“Padahal masyarakat itu pemilik tanah secara adat, tetapi tidak punya akses perizinan,” ujarnya.
Menurut Ali, jika Bandhayo Poboide atau kerapatan adat dirumuskan kembali, maka izin-izin pengelolaan sumber daya bisa dibahas dan direkomendasikan melalui kewenangan adat. Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam kerangka negara kesatuan, perizinan tetap berada di bawah otoritas pemerintah pusat. Namun, pertimbangan adat seharusnya menjadi rujukan utama sebelum izin diterbitkan.
Ia menegaskan, yang harus menjadi prioritas adalah kepentingan rakyat sebagai pemilik tanah, bukan semata investor. Bandhayo Poboide, kata dia, dapat melahirkan rumusan atau regulasi, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya aktivitas pertambangan.
Dalam struktur adat, kerapatan tersebut dinaungi oleh empat unsur utama yakni, buatula syara, buatula bubato, buatula bandhayo, dan buatula bala. Keempat pilar ini, menurutnya, dapat melibatkan para ahli termasuk pakar geologi yang dalam istilah adat disebut sebagai orang yang berada di luar bangsal untuk memberikan pertimbangan teknis sebelum suatu wilayah dibuka untuk tambang.
Ali juga menekankan pentingnya musyawarah adat di setiap wilayah. Di Suwawa, misalnya, perlu ada Bandhayo Poboide karena terdapat dua pohala’a, yakni Suwawa dan Bulango.
Di Kota Gorontalo dan Pohuwato terdapat Bandhayo Poboide Dulohupa, di Gorontalo Utara ada Bandhayo Boidu, dan di Limboto terdapat Bandhayo Limutu.
Ia bahkan mendorong agar Pohuwato dikukuhkan sebagai tanah adat yang tidak bisa dirusak secara sembarangan.
Menurutnya, jika struktur adat kembali ditegakkan, maka akan lahir hukum-hukum adat yang mampu membatasi eksploitasi agar tidak berlangsung masif dan merusak.
Ia mencontohkan praktik di sejumlah wilayah di Kalimantan, di mana investor harus terlebih dahulu meminta izin kepada kerapatan adat sebelum masuk ke suatu wilayah. “Investor harus permisi kepada kerapatan adat, karena merekalah yang mengetahui dan menjaga wilayah itu,” katanya.
Ali juga menyinggung soal penggunaan alat berat dalam pertambangan rakyat. Dalam konsep adat dikenal istilah “de ja potolonggalo” (tidak menimbulkan keributan). Artinya, aktivitas pengelolaan sumber daya tidak boleh memicu kerusakan atau kegaduhan, termasuk kebisingan dan dampak besar seperti penggunaan ekskavator. Dalam tradisi lama, penggalian dilakukan dengan alat sederhana dan tetap memperhatikan keseimbangan alam.
Ia menilai kerusakan pegunungan dan perbukitan yang terjadi saat ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap rambu-rambu adat, termasuk penggarapan tanah adat tanpa batas yang jelas. Jika tidak dibatasi, menurutnya, eksploitasi ini berbahaya bagi Pohuwato dan daerah lain yang memiliki potensi pertambangan.
Karena itu, Ali mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengaktifkan kembali lembaga adat serta melakukan pemetaan wilayah adat yang harus dilindungi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah, termasuk di Pohuwato, seharusnya tidak sembarangan menerbitkan izin pertambangan karena wilayah tersebut merupakan bagian dari tanah adat Hulonthalangi.
Menurutnya, penguatan kembali struktur kerapatan adat dengan Gubernur sebagai olongia lolipu, bupati/wali kota sebagai ta uwa lo lipu, camat sebagai uleya lo lipu, kepala desa sebagai puluwa lo lipu, dan kepala dusun sebagai talenga lo lipu, perlu segera direvitalisasi.
Struktur ini tidak hanya mengurus soal tambang, tetapi juga aspek sosial lain seperti musyawarah adat, pernikahan, hingga solidaritas sosial dalam masyarakat.
“Kalau tidak segera dibatasi, eksploitasi ini bisa menjadi ancaman serius bagi Pohuwato dan daerah pertambangan lainnya,” tandasnya.
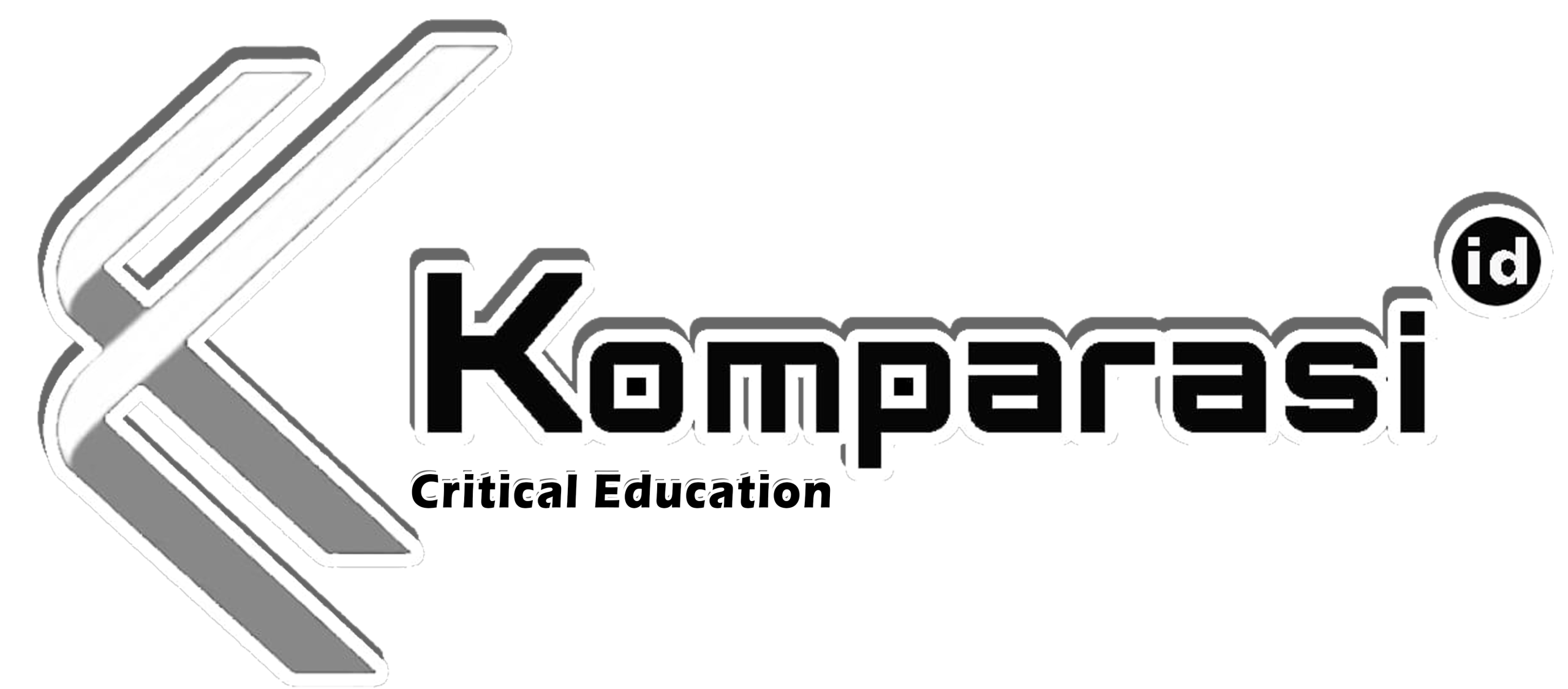








Leave a Reply