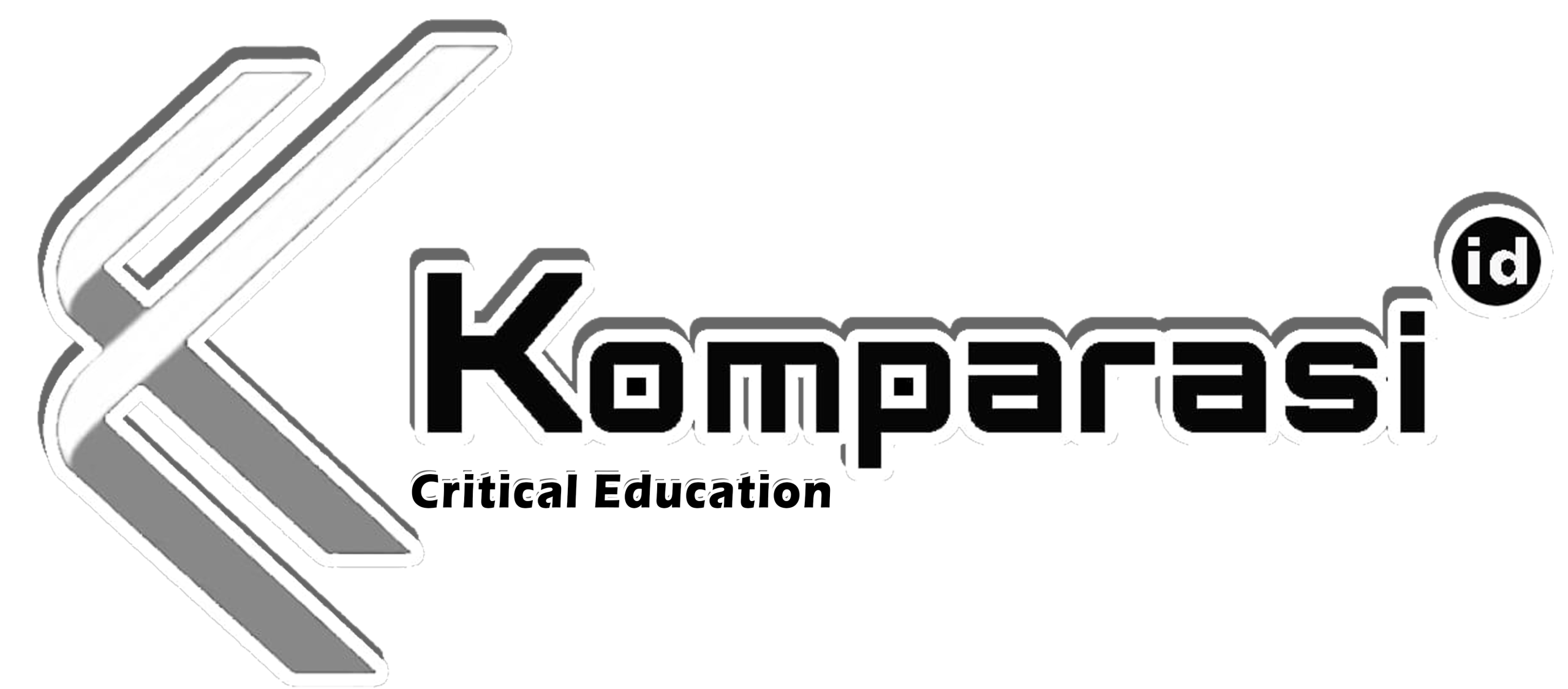KOMPARASI.ID – Politik adalah jalan untuk menghasilkan kebaikan bersama. Begitulah khutbah dari Aristoteles di masa yang lampau.
Ucapan itu seakan menjadi aksioma ajaib yang digunakan untuk membangun teori-teori politik setelahnya, sampai hari ini. Sebuah ikhtiar mahkluk berakal yang terus menerus percaya bahwa ada kebaikan dalam politik.
Kenyataannya, keterangan-keterangan teoritis dari para pemikir itu, selalu dilecehkan oleh para politisi.
Tanpa otak, hanya bermodalkan amplop, mereka terjun dalam gelanggang politik demi satu misi: kekuasaan murni. Kekuasaan bukanlah alat, melainkan alat sekaligus tujuan. Itulah motif sebenarnya dari politisi.
Begitu juga dengan kata “demokrasi”. Mereka, para politisi itu, seenaknya mengartikan demokrasi semata-semata pemilihan umum.
Dengan wawasan yang lebih kecil dari kotak TPS, namun penuh siasat, mereka menunggangi masyarakat yg tak terdidik secara politik demi ambisi kekuasaan, meskipun itu sanak saudara mereka sendiri.
Hal inilah yang sering terjadi di area pinggiran yang jauh dari pusat-pusat peradaban dan kekuasaan.
Para politisi di sini, tidak memiliki komitmen untuk mendidik masyarakat. Bagi mereka yang penting mereka punya uang dan mempunyai hubungan kekerabatan, garis ayah maupun ibu, yang berjumlah banyak. Itu adalah modal utama. Tak peduli apakah anda itu paham demokrasi atau tidak.
Kondisi dan struktur masyarakat yang rata-rata masih bermental feodal, miskin, dan berpendidikan rendah, kemudian oleh para politisi itu memanfaatkan kelemehan-kelemahan itu untuk menebar panji-panji marga untuk menggaet dukungan.
Sisanya adalah dengan cara dibeli dengan serangan fajar atau dengan sistem politik klientalime. Tidak ada perjuangan ideologis. Hal ini banyak terjadi baik dalam pilkada maupun pileg.
Terlepas dari kondisi ini, mestinya demokrasi tidak boleh dioperasikan demikian, sebab demokrasi dijalankan dengan dasar bahwa setiap orang adalah warga negara yang setara, dan memilih pemimpin setara dengan memilih gagasan mana yang dinilai menguntungkan bagi kehidupan bersama.
Tapi rupanya masyarakat kita, belum bisa memikirkan hal-hal yang menyangkut sistem. Yang mereka tahu, bahwa mereka bisa makan, minum, dan tenang. Sisanya bukan urusan mereka.
Jelas ini adalah bentuk apatisme yg tidak diharapkan dalam demokrasi. Sebab, salah satu pilar tegaknya nilai-nilai demokrasi adalah masyarakat yang kuat, lebih tepatnya, proaktif dalam mengawal proses politik.
Hanya saja, para politisi ini, dengan sengaja memanfaatkan, juga turut memelihara, kedangkalan-kedangkalan publik, agar bisa melanggengkan kekuasaan.
Hal Itu terlihat, di mana mereka dalam agenda-agenda formal maupun informal, para politisi hanya mengkampanyekan, bahwa saya punya hubungan darah dengan si A, si B, dan seterusnya. Atau, bahwa si A tidak ikut melayat dipemakam so B, jadi tidak usah dipilih. Itu adalah fakta, bagaimana para politisi menerapkan kampanye yang tidak sehat. Alih-alih kampanye, itu adalah model pembodohan.
Gagasan yang harusnya jadi tolok ukur utama dalam ranah ini namun seakan dihilangkan esensinya, yang ada hanyalah serangan-serangan personal yang memupuk kebencian antara warga negara.
Akhirnya, kerukunan rusak, dan kalaupun mereka menang, yang menang adalah kelompoknya sendiri, sedang masyarakat tetaplah orang miskin dan buta huruf terhadap politik, plus kekeluargaan yg rusak.
Fakta ini jelas tidak sejalan dengan ide demokrasi. Praktek-praktek semacam ini, adalah akar korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ini merupakan penyakit bangsa ini yang belum bisa diobati dengan reformasi. Hal inilah yang menyebabkan bagaimana fenomena “orang dalam” menjamur dalam birokrasi pemerintahan;
bagaimana proyek-proyek bantuan hanya terfokus pada beberapa kelompok saja; juga bisa memicu politik dinasti dalam politik.
Di sisi lain, hal tersebut menyebabkan lembaga pemerintahan tidak dijalankan dengan sistem meritokrasi (di mana jabatan dijalankan atas dasar kemampuan, bukan kedekatan).
Akhirnya, lumpuhnya fungsi chake and balances dalam cabang kekuasaan tidak terelakkan lagi, seperti sekarang ini.
Lebih jauh, masyarakat tetap dilemahkan dalam posisinya sebagai kelompok mayoritas kelas bawah yang rentan.
Mereka tetap dengan kemiskinan dan kebodohannya, sebab masyarakat yang lemah lebih mudah diarah-arahkan dari pada masyarakat yang kuat ekonomi dan pendidikan. Hal inilah yang terus dipelihara elit dalam sistem politik kita.
Pada akhirnya, yang kita sebut “pesta demokrasi” hanya menjadi ajang hiburan semu bagi masyarakat. Tidak ada dampak yang berarti bagi pendidikan dan kesejahteraan mereka.
Rakyat hanyalah petugas yang membersihkan sampah pesta setelah para elit selesai bagi-bagi kue kekuasaan. Begitulah demokrasi di pinggir peradaban hari-hari ini: meresahkan sekaligus menggelikan.
Disclaimer:
Artikel ini adalah Opini penulis. Segala materi yang ditulis adalah tanggung jawab penulis dan tidak mewakili redaksi Komparasi.id