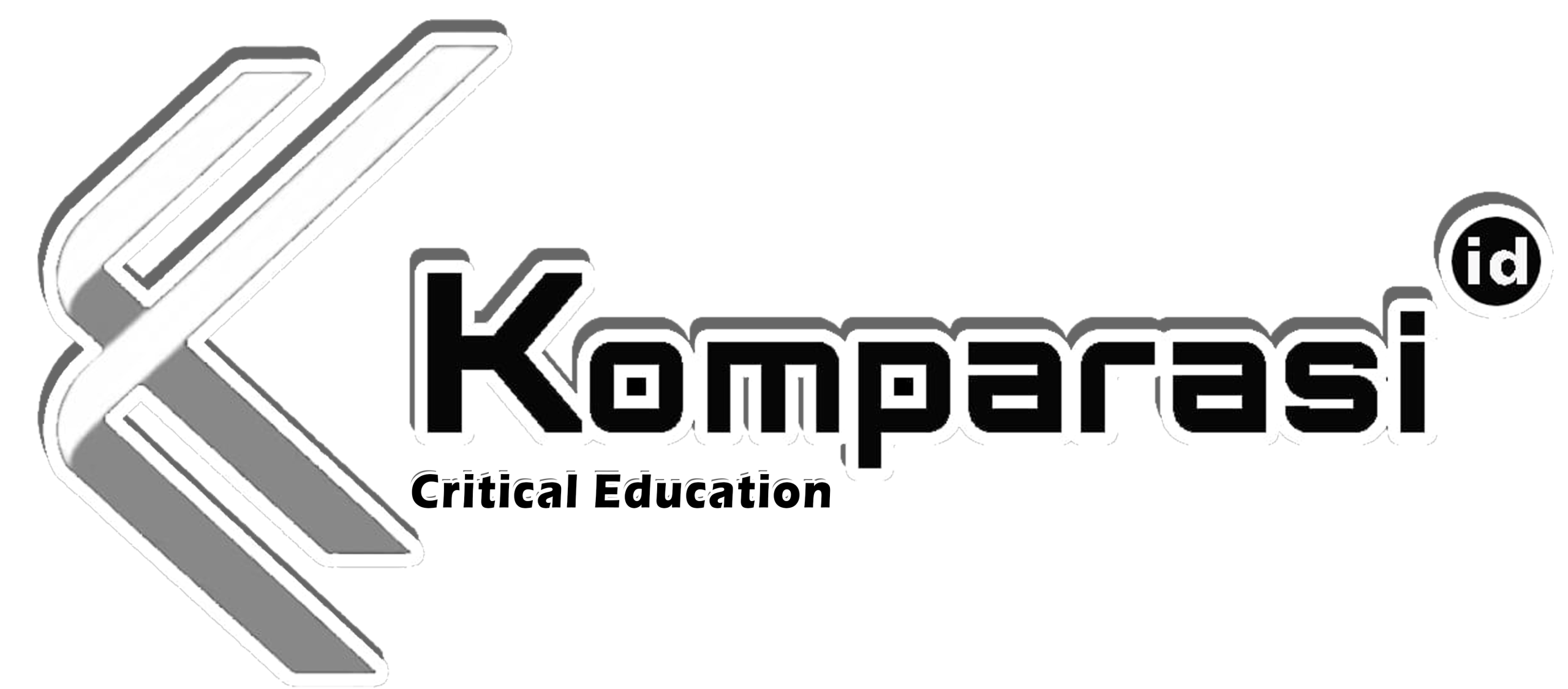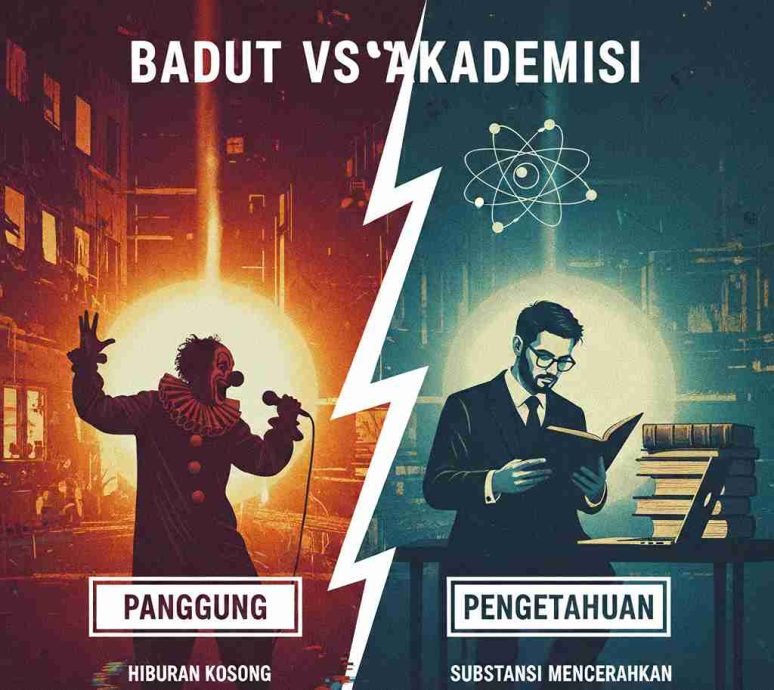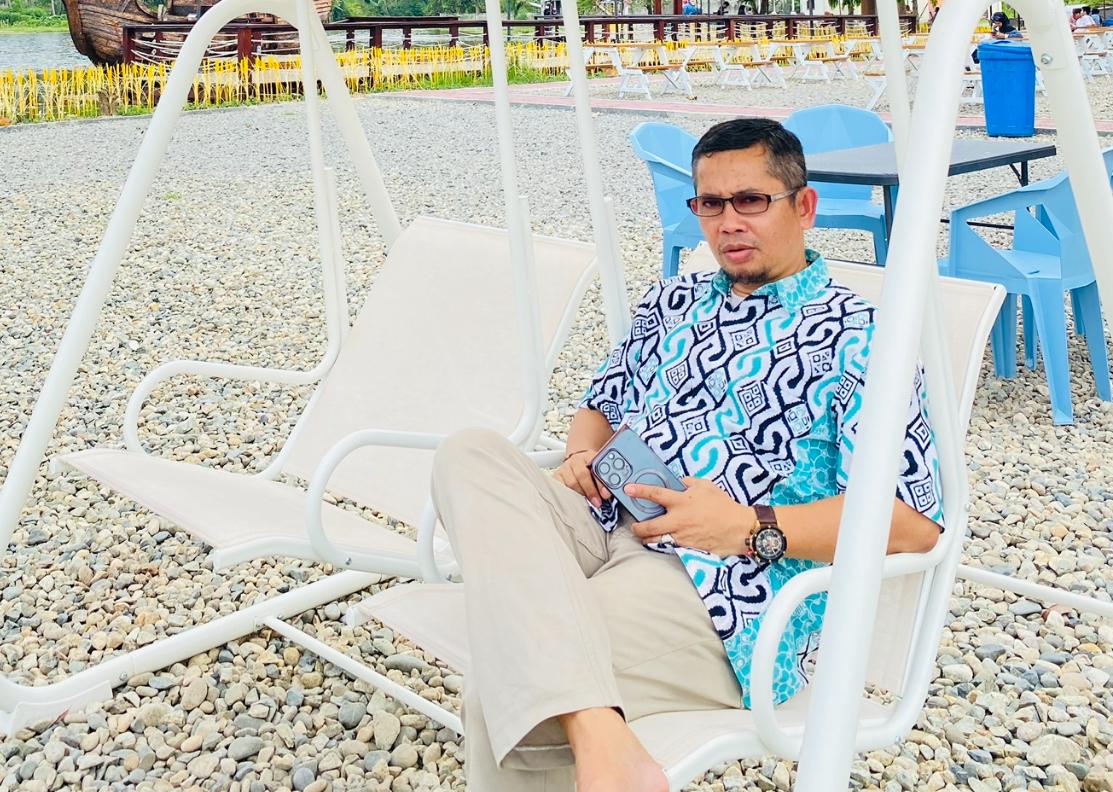KOMPARASI.ID – Dalam beberapa tahun terakhir, publik kian sering disuguhi wajah-wajah yang muncul di layar kaca atau kanal digital bukan karena kapasitas intelektualnya, melainkan karena kemampuan mereka menarik perhatian.
Sosok-sosok yang sebelumnya dikenal sebagai orang biasa atau selebritas, atau figur viral tiba-tiba menjadi komentator politik, analis sosial, bahkan pengamat kebijakan.
Fenomena ini menandai pergeseran serius dalam praktik jurnalistik, popularitas kini mengalahkan kapasitas.
Media seolah terjebak dalam logika algoritma, di mana klik, tayangan, dan viralitas lebih penting daripada substansi.
Dalam proses itulah, ruang publik kehilangan kedalaman, dan diskursus serius berubah menjadi tontonan ringan.
Sosok yang seharusnya menjadi penghibur kini didorong memerankan peran sebagai politisi atau pakar dadakan seperti bahasanya “badut yang dipaksa jadi politikus.”
Ketimpangan dan Krisis Representasi
Masalah kredibilitas narasumber bukan hanya soal kapasitas individu, tetapi juga soal representasi dan seleksi.
Riset Tempo Institute dan Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) menunjukkan bahwa dari sekitar 22.900 narasumber media di Indonesia, hanya 11 persen yang perempuan.
Data ini diambil dari riset terhadap 7 media cetak dan 3 media daring pada 6 Agustus – 6 September 2018 (sumber: Tempo Institute via BAKTI News).
Angka tersebut menggambarkan bias dalam representasi narasumber dan menunjukkan bahwa seleksi figur di media belum berlandaskan kompetensi yang merata.
Representasi yang timpang berarti keragaman sudut pandang juga terbatas. Hal serupa ditemukan dalam riset Remotivi (2021) tentang isu inklusivitas di media.
Penelitian itu mencatat bahwa narasumber dari kelompok “non-marginal” yakni kelompok yang sudah dominan di masyarakat mengisi sekitar 80,8 persen ruang narasumber, sedangkan kelompok marginal hanya 18,7 persen (sumber: Konde.co).
Artinya, suara dari kelompok yang terpinggirkan dalam isu publik masih sulit menembus ruang pemberitaan.
Media lebih memilih figur mapan atau terkenal ketimbang mereka yang benar-benar memahami isu di lapangan.
Kualitas Berita dan Kepercayaan Publik
Fenomena ini berimbas langsung pada kualitas pemberitaan dan kepercayaan publik terhadap media.
Penelitian Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) tentang kualitas berita televisi menemukan bahwa aspek “objektivitas” dan “gambaran realitas” masih tergolong lemah salah satu penyebabnya adalah dominasi narasumber yang tidak proporsional atau tidak relevan dengan isu yang dibahas (sumber: Jurnal UNIBI).
Ketika media mengandalkan sumber yang sama, atau sekadar figur populer, perspektif yang muncul menjadi dangkal dan berulang.
Hal serupa juga disoroti dalam penelitian Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang menelaah pola pemberitaan media selama pandemi.
Penelitian itu menemukan adanya “dominasi sumber informasi”, yaitu media yang terlalu sering mengutip sumber dari kelompok atau instansi yang sama, sehingga keberagaman dan kedalaman informasi menurun (sumber: Journal UNY).
Ini menunjukkan bahwa tekanan kecepatan produksi berita dan algoritma digital membuat redaksi sering memilih narasumber yang mudah diakses, bukan yang paling memahami konteks.
Padahal, survei Katadata DataBoks (2023) memperlihatkan bahwa anak muda Indonesia justru menjadikan kredibilitas sebagai faktor utama dalam memilih sumber berita.
Sebanyak 55 persen responden menyatakan “kepercayaan terhadap kredibilitas sumber” menjadi alasan utama mereka membaca berita (sumber: Katadata DataBoks).
Kenyataan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ekspektasi publik dan praktik media. Masyarakat ingin sumber kredibel, sementara media sering menampilkan figur yang viral.
Ruang Publik yang Semakin Dangkal
Ketika figur populer lebih sering tampil ketimbang pakar, ruang publik kehilangan fungsinya sebagai arena pendidikan warga. Diskusi serius soal kebijakan publik berubah menjadi hiburan massal.
Komentar-komentar ringan yang viral lebih banyak mengisi ruang pemberitaan daripada pandangan akademis yang memberi arah.
Fenomena ini bukan hanya melemahkan kualitas debat publik, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap media sebagai institusi pengetahuan.
Namun, tanggung jawab tidak sepenuhnya ada pada media. Publik juga berperan dalam membentuk selera informasi.
Selama audiens lebih memilih sensasi daripada substansi, media akan terus memproduksi apa yang paling cepat dikonsumsi, bukan yang paling layak didengar.
Menemukan Kembali Tanggung Jawab Jurnalistik
Jurnalisme sejatinya berdiri di atas dua nilai, kapasitas dan kredibilitas. Popularitas mungkin membantu menarik perhatian, tetapi tanpa kompetensi, ruang publik hanya akan dipenuhi suara-suara tanpa arah.
Sudah saatnya redaksi kembali memegang disiplin verifikasi dan seleksi narasumber. Narasumber bukan hanya pengisi kutipan, tapi penentu arah pengetahuan publik.
Krisis kredibilitas media bukan semata akibat kehadiran “badut yang dipaksa jadi politikus”, melainkan akibat sistem yang membiarkan panggung informasi dikuasai oleh mereka yang paling keras suaranya bukan yang paling tahu persoalannya.