KOMPARASI.ID – Sungai Kuantan, Riau, sore itu berkilau keemasan. Dari tepian Narosa, ribuan orang berdesakan, berebut posisi terbaik untuk menyaksikan Pacu Jalur 2025.
Tradisi lomba perahu panjang yang sudah ada lebih dari seabad ini bukan sekadar hiburan.
Bagi masyarakat Kuantan Singingi, ia adalah denyut kehidupan, ritual tahunan yang menandai identitas kolektif mereka.
Dentuman gendang, teriakan pendukung, dan deru dayung yang membelah sungai memenuhi udara.
Aroma sungai yang basah dan tanah lembap berpadu dengan bau asap dari pedagang kaki lima yang menawarkan jagung bakar dan minuman kelapa muda.
Semua panca indera seakan disibukkan dalam satu harmoni yang khas.
Namun, bukan hanya perahu yang mencuri perhatian. Di sisi arena, sebuah panggung budaya menyala, menampilkan sekelompok pemuda dengan pakaian adat berwarna mencolok.
Mereka bergerak dengan luwes, mengikuti irama musik tradisional, memadukan gerakan tari Bugis-Makassar dengan tarian modern yang disesuaikan untuk panggung terbuka.
Sorak-sorai penonton sejenak terhenti. Budaya Sulawesi Selatan hadir di tengah gemuruh Pacu Jalur, memberi warna baru pada festival yang sudah mendunia ini.
Di balik penampilan itu, berdiri Daeng Supriansyah, Ketua Koordinator Bugis-Makassar di Riau.
Sejak beberapa minggu sebelum acara, ia sibuk mengoordinasikan timnya, memilih penari, menyiapkan kostum, bahkan menyesuaikan gerakan agar terlihat menarik di panggung yang besar.
Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, memperkenalkan budaya leluhur Sulawesi Selatan di tengah tradisi yang sudah begitu melekat di Kuansing.
“Terima kasih kepada semua pihak, khususnya warga Sulawesi Selatan yang sudah mendukung kami. Dengan dukungan itu, kami bisa tampil maksimal dan menunjukkan versi terbaik dari budaya kami,” ujarnya dengan mata berbinar, menandakan kebanggaan yang tulus.

Ruang Budaya di Tengah Tradisi
Pacu Jalur sejak lama dikenal sebagai pesta rakyat. Perahu panjang yang ditumpangi puluhan pendayung bukan hanya tentang kecepatan.
Ia tentang kerja sama, strategi, dan daya tahan fisik.
Namun, belakangan, Pacu Jalur juga menjadi panggung budaya yang mendunia. Tahun ini, gaungnya semakin luas setelah tarian “Aura Farming” viral di media sosial.
Penonton dari berbagai provinsi, bahkan mancanegara, hadir untuk menyaksikan.
Dalam suasana meriah itu, tampilnya budaya Sulawesi Selatan menjadi titik fokus yang memikat.
Kain adat berkibar, langkah penari rapi, dan ekspresi penonton yang terpaku membuat momen ini hangat dan sarat makna.
Seolah-olah, budaya perantau dan tradisi lokal sedang saling bersapa dalam satu ruang publik.
“Harapannya, budaya Sulawesi Selatan selalu punya tempat di setiap event besar di Riau,” kata Supriansyah.
Baginya, penampilan ini bukan sekadar hiburan, ia adalah usaha menjaga identitas dan akar budaya agar tetap hidup, sekaligus memberi inspirasi bagi generasi muda perantau.

Jejak Dukungan dan Semangat Komunitas
Supriansyah tidak berjalan sendiri. Sejumlah tokoh Bugis-Makassar hadir di tepian Narosa, memberikan semangat bagi generasi muda yang menari di panggung.
Salah satunya Daeng Amiruddin Sijaya, yang sejak lama konsisten mendorong agar budaya perantau tetap eksis di tanah rantau.
Kehadiran mereka bukan sekadar simbol, melainkan pengingat bahwa tradisi harus dihidupkan bersama-sama.
Dalam kerumunan, terlihat pula keluarga, anak-anak, dan warga lokal yang menyaksikan dengan kagum.
Beberapa dari mereka merekam pertunjukan dengan ponsel, sementara yang lain berdiri terpaku, menikmati setiap gerakan dan warna kostum.
Suasana itu menciptakan dialog tak langsung antara tradisi lokal dan budaya perantau, sebuah momen di mana Pacu Jalur menjadi jembatan keberagaman.

Panggung di Sungai dan Nilai Simbolik
Hari itu, Sungai Kuantan bukan sekadar arena lomba. Sungai menjadi panggung, tempat di mana kerja sama pendayung, irama tarian, dan sorak-sorai penonton bersatu.
Setiap dayung yang membelah air, setiap langkah penari yang diulang puluhan kali, semuanya bercerita tentang identitas, sejarah, dan kebanggaan.
Menurut Supriansyah, momen ini penting bagi generasi muda perantau.
“Kami ingin mereka tahu bahwa budaya kita bisa tampil di mana saja. Tidak perlu menunggu di kampung halaman. Budaya bisa hidup berdampingan dengan tradisi orang lain,” katanya.
Bagi penonton, ini bukan sekadar pertunjukan. Ini adalah pengalaman langsung merasakan keberagaman Nusantara.
Suasana tepi sungai yang ramai, campuran aroma, suara, dan warna, membuat Pacu Jalur 2025 terasa lebih dari sekadar lomba mendayung ia adalah perayaan identitas yang hidup, merangkul, dan menyatukan.

Tradisi yang Merangkul Keberagaman
Di ujung sore, saat cahaya matahari mulai redup dan perahu terakhir mencapai garis finis, tepuk tangan dan sorak-sorai penonton masih bergema.
Sungai Kuantan telah menyaksikan lebih dari lomba kecepatan. Ia menjadi jembatan budaya, menyatukan masyarakat lokal dan perantau.
Pacu Jalur 2025 menunjukkan bahwa tradisi bisa lebih dari ritual tahunan. Ia bisa menjadi ruang pertemuan antarbudaya, panggung bagi identitas perantau, dan sarana merayakan keberagaman Indonesia dalam satu momen.
Supriansyah menatap panggung dengan bangga. Ia tahu, di balik gerakan tarian, kostum, dan senyum penonton, ada pesan penting. Budaya adalah jembatan, bukan batas.
Hari itu, Sungai Kuantan membuktikan pesan itu dengan cara yang paling nyata melalui perahu, tarian, dan ribuan mata yang menyaksikan.

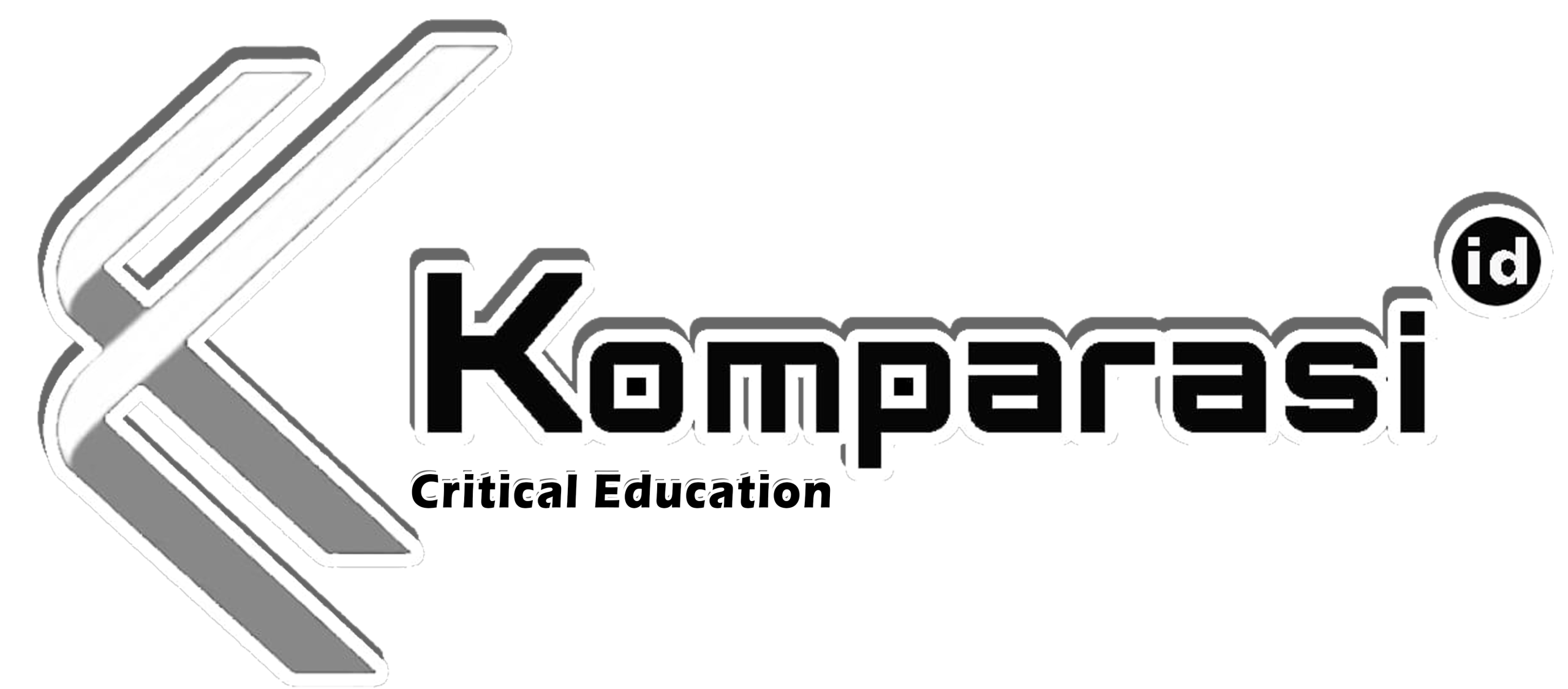






Leave a Reply