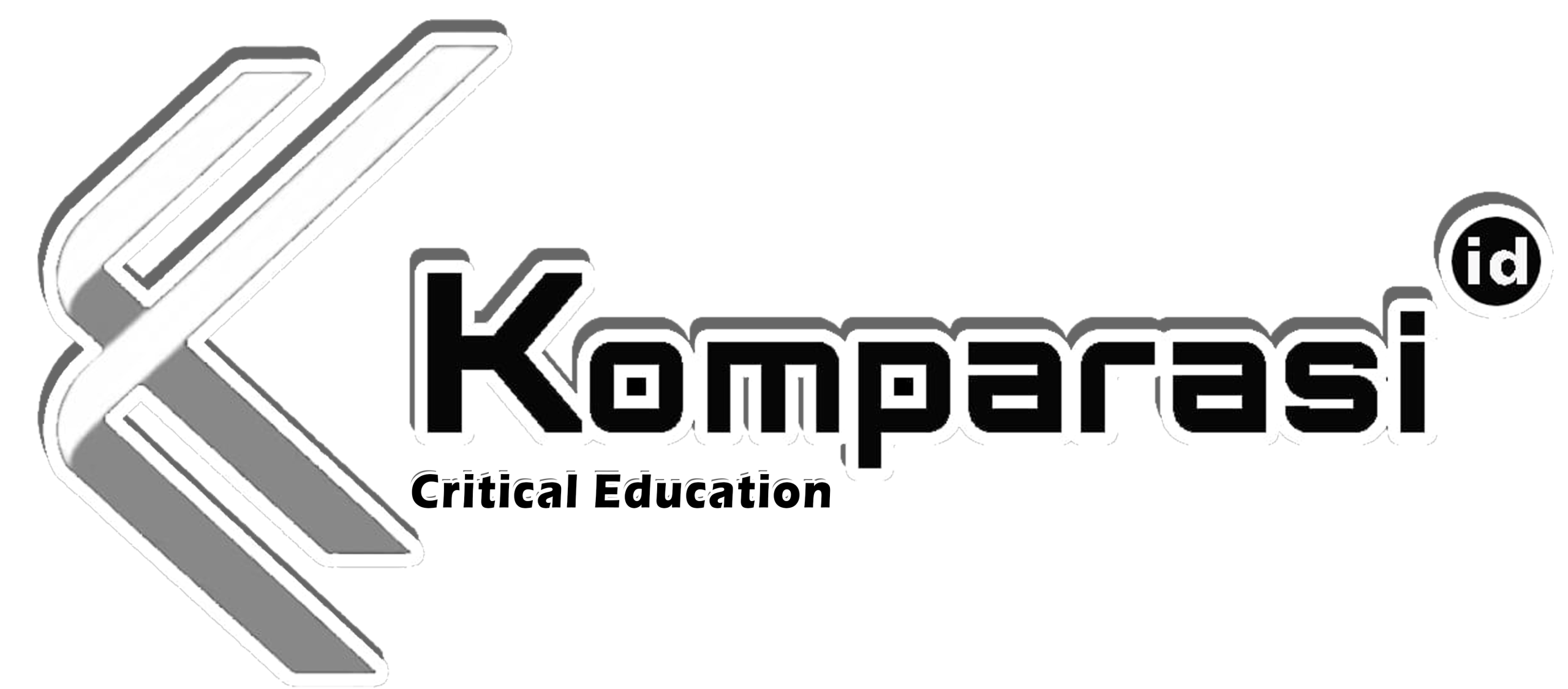Oleh: Mega A.D. Mokoginta – Aktivis Perempuan dan Penggiat Sosial.
KOMPARASI.ID – Di tengah riuh propaganda kemajuan dan proyek-proyek pembangunan yang dirayakan di layar kaca, ada satu ironi yang terus menganga seperti luka yang tak pernah sembuh: ketimpangan pendidikan.
Anak-anak kota mengecap teknologi dalam genggaman, belajar dari layar digital, namun di sudut negeri yang jauh, masih ada anak-anak yang belum pernah menyentuh buku—membaca pun tertatih, tapi mereka punya mimpi, dan mimpi itu tak pernah kecil.
Pendidikan, yang seharusnya menjadi hak kodrati, masih terbelenggu dalam pagar geografis, kasta sosial, dan logika ekonomi.
Pendidikan tidak lahir dari ruang kosong. Ia bukan sekadar lembaga, kurikulum, atau rapor yang digantung di dinding rumah.
Pendidikan adalah proses menjadi manusia—humanisasi, sebagaimana digugat oleh Paulo Freire.
Dalam Pedagogy of the Oppressed, Freire menolak model pendidikan banking system yang menjadikan murid sekadar celengan kosong.
Ia menuntut agar pendidikan menjadi medium pembebasan: ruang dialog yang membangkitkan kesadaran, bukan membius dengan dogma.
Maka memperjuangkan pendidikan yang adil bukan hanya soal distribusi fasilitas, tapi pertaruhan atas harkat manusia.
Namun faktanya, wajah pendidikan kita masih bercermin pada eksklusivitas. Anak-anak yang dilahirkan di daerah terpinggirkan, seolah dipaksa membayar lebih mahal hanya untuk menatap masa depan.
Mereka harus bertarung dengan jarak, cuaca, bahkan ketidakhadiran guru. Ketika sinyal adalah barang mewah dan cahaya listrik hanya hadir sesekali, maka pertanyaan yang harus kita ajukan bukan sekadar teknis, tapi etis: di manakah keadilan dalam sistem pendidikan kita?
Immanuel Kant menyatakan, “Manusia hanya bisa menjadi manusia melalui pendidikan.” Kutipan ini tidak sekadar estetika intelektual; ia adalah pernyataan ontologis.
Pendidikan bukan hanya tentang transmisi keterampilan, tetapi soal bagaimana individu membentuk kesadaran moral dan rasionalitas.
Maka jika anak-anak di pelosok tak mendapat pendidikan yang layak, kita tidak sekadar merampas kesempatan, tapi mengingkari hak mereka untuk menjadi manusia seutuhnya.
Pendidikan sejatinya adalah jembatan: antara kenyataan dan harapan, antara kini dan nanti.
Mendirikan sekolah di pelosok bukanlah proyek fisik semata, tetapi pembangunan simbolik atas masa depan yang lebih adil.
Di balik papan tulis yang retak dan kursi kayu yang berderit, bersembunyi potensi untuk mengubah arah sejarah.
Lebih dari itu, pendidikan adalah tindakan politik. Ia tidak pernah steril dari kekuasaan.
Dalam kelas-kelas kosong yang ditinggal guru, dan dalam ruang-ruang belajar yang membisu, sesungguhnya sedang bekerja keputusan struktural yang menentukan siapa yang akan tumbuh, dan siapa yang akan dilupakan.
Maka memperjuangkan pendidikan yang merata bukan sekadar kerja sosial, tapi laku politis untuk merobohkan ketimpangan yang dibungkus rapi oleh birokrasi.
Hari Anak Nasional bukan sekadar seremoni. Ia adalah peringatan bahwa anak-anak bukan “calon manusia”, melainkan manusia sepenuhnya—hari ini. Mereka tidak bisa menunggu sistem membaik.
Kitalah yang harus memperbaiki sistemnya. Pendidikan tidak bisa digantungkan pada kementerian semata; ia adalah urusan kolektif, kerja kebangsaan.
Kita perlu membongkar paradigma lama. Pendidikan bukan hanya soal investasi ekonomi, tetapi ekspresi dari cinta dan nilai kemanusiaan.
Sebab hanya dengan cinta—cinta yang aktif, cinta yang membebaskan, sebagaimana dikatakan Freire—pendidikan dapat mengubah.
Maka mendidik anak di pelosok bukanlah kemurahan hati, tetapi keberanian untuk menyatakan bahwa semua manusia layak tumbuh dalam martabat.
Di tengah dunia yang terus berlari mengejar modernitas, mari kita menoleh ke pinggir: ke suara-suara lirih dari ujung negeri.
Suara anak-anak yang ingin belajar, ingin tahu, dan ingin bermimpi. Kita harus menjawab suara itu, bukan dengan wacana, tapi dengan komitmen konkret: tak boleh ada lagi anak yang tertinggal hanya karena ia lahir di tempat yang jauh dari pusat.
Sebab harapan bukan milik segelintir. Harapan adalah milik semua anak. Membebaskan mereka untuk bermimpi dan menyusun masa depan dengan imajinasi—itulah tugas kita sebagai manusia yang berpikir dan berbelas kasih.
Disclaimer:
Artikel ini adalah Opini penulis. Segala materi yang ditulis adalah tanggung jawab penulis dan tidak mewakili redaksi Komparasi.id